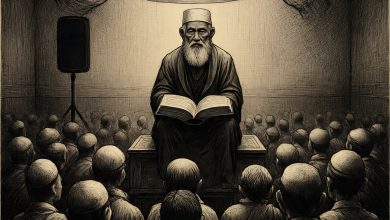Post-Democracy: Antara Ritual Demokratis dan Kuasa Oligarki

Konsep Post-Democracy pertama kali dipopulerkan oleh Colin Crouch melalui bukunya Post-Democracy (2004), sebagai refleksi kritis atas transformasi demokrasi liberal di era kapitalisme lanjut. Crouch menggarisbawahi bahwa meski institusi dan prosedur demokratis formal tetap dipertahankan, esensinya mengalami erosi akibat dominasi oligarki ekonomi dan pengaruh korporasi terhadap kebijakan publik. Dalam rezim post-democratic, pemilu masih dilaksanakan, partai politik masih eksis, dan wacana publik masih berlangsung, tetapi keputusan politik substantif semakin dikendalikan oleh aktor-aktor yang tidak dipilih secara demokratis, khususnya elite ekonomi global dan aktor pasar.
Dari Demokrasi Prosedural ke Post-Democracy
Demokrasi, sebagaimana dipahami secara konvensional, mengandung dua dimensi: prosedural dan substantif. Dimensi prosedural menekankan pada mekanisme pemilihan umum, keterwakilan, dan aturan main formal yang mengatur relasi antara negara dan warga negara. Sementara demokrasi substantif menekankan pada kualitas partisipasi politik, distribusi keadilan sosial, dan perlindungan terhadap kelompok rentan.
Crouch menunjukkan bahwa dalam fase post-democratic, dimensi prosedural tetap dipertahankan sebagai bentuk legitimasi simbolik, tetapi dimensi substantif terkikis oleh dominasi modal dan teknik manajerial dalam pengambilan kebijakan. Partisipasi politik warga semakin terbatas pada ritual elektoral, sementara arah kebijakan semakin ditentukan oleh lobbyist, teknokrat, dan korporasi transnasional.
Korporatisme Baru dan Depolitisasi Publik
Salah satu ciri penting post-democracy adalah apa yang Crouch sebut sebagai new corporatism—yakni bentuk relasi antara negara dan pasar yang memungkinkan korporasi besar mengintervensi proses legislatif dan birokratis. Proses politik dikemas dalam bahasa teknokratis, menciptakan ilusi bahwa kebijakan adalah produk “rasionalitas objektif”, padahal sarat kepentingan ekonomi.
Fenomena ini bersinggungan dengan kritik Wendy Brown dan Michel Foucault terhadap neoliberal governmentality, di mana pasar tidak lagi sekadar sistem ekonomi, tetapi menjadi rasionalitas yang mengatur kehidupan sosial dan institusi politik. Dalam kerangka ini, warga negara direduksi menjadi “konsumen kebijakan”, bukan lagi subjek politik aktif.
Keterasingan Partai Politik dan Krisis Representasi
Partai politik, sebagai institusi kunci dalam demokrasi, dalam rezim post-democratic justru mengalami paradoks. Di satu sisi, mereka tetap menjadi mediator antara rakyat dan negara; di sisi lain, mereka kehilangan akar sosialnya akibat proses profesionalisasi dan komersialisasi politik. Kampanye politik lebih banyak ditentukan oleh konsultan, survei opini, dan strategi komunikasi pemasaran ketimbang program ideologis.
Akibatnya, terjadi jarak yang semakin lebar antara rakyat dan elite politik, menciptakan apa yang disebut sebagai “krisis representasi”. Kepercayaan publik terhadap partai menurun, tetapi tidak diimbangi oleh mekanisme partisipatif alternatif yang mampu mengisi kekosongan tersebut.
| Unsur / Konsep Kunci | Penjelasan Ringkas | Kutipan Langsung (Crouch) | Karya & Tahun |
|---|---|---|---|
| 1. Form Without Substance | Demokrasi tetap berjalan secara prosedural, tapi kehilangan makna substantif. | “We operate a model of democracy that is for the most part a formal shell.” | Post-Democracy, 2004 |
| 2. Corporate Capture | Korporasi besar mengendalikan kebijakan dan menggantikan peran warga. | “Public debate is largely a spectacle managed by professional experts.” | Post-Democracy, 2004 |
| 3. Depoliticization | Warga makin apatis; partisipasi politik digantikan oleh konsumsi. | “Public involvement in politics is mainly confined to voting in elections.” | Post-Democracy, 2004 |
| 4. Elitism of Political Class | Politisi tidak mewakili rakyat, tetapi menjadi bagian dari elit teknokratik. | “Policies are increasingly shaped by the interests of a narrow elite.” | Post-Democracy, 2004 |
| 5. Professionalized Politics | Politik menjadi domain profesional yang terpisah dari kehidupan rakyat sehari-hari. | “The electorate is... a target for marketing, not a body to be engaged with.” | Post-Democracy, 2004 |
Kontekstualisasi di Indonesia
Dalam konteks Indonesia, gejala post-democracy tampak jelas dalam beberapa aspek:
Komersialisasi pemilu: Kontestasi politik lebih ditentukan oleh kapasitas modal, bukan kualitas gagasan. Biaya politik yang tinggi memicu patronase dan korupsi struktural.
Dominasi oligarki politik-ekonomi: Kartel politik, penguasaan media oleh elite bisnis-politik, dan hubungan simbiotik antara politisi dan pengusaha menciptakan ruang demokrasi yang semu.
Keterbatasan partisipasi warga: Partisipasi politik masih bersifat seremonial, terfokus pada pemilu, dan minim kanal deliberatif yang memungkinkan warga mengartikulasikan aspirasi secara substansial.
Fenomena ini diperkuat oleh infrastruktur digital yang mempercepat sirkulasi informasi, tetapi juga memperdalam polarisasi dan manipulasi emosi massa melalui disinformasi dan political branding.
Kritik dan Alternatif
Meskipun analisis post-democracy sangat tajam dalam membongkar paradoks demokrasi kontemporer, sejumlah kritik muncul dari berbagai perspektif. Sebagian sarjana menilai bahwa Crouch terlalu pesimis dan mengabaikan potensi resistensi masyarakat sipil. Di banyak negara, muncul inisiatif grassroots, gerakan sosial digital, dan partisipasi deliberatif sebagai bentuk reaksi terhadap stagnasi demokrasi representatif.
Pendekatan agonistic pluralism dari Chantal Mouffe misalnya, menawarkan pembacaan alternatif yang melihat konflik sebagai bagian esensial dari demokrasi. Mouffe menolak demokrasi yang terlalu menekankan konsensus teknokratis, dan sebaliknya mendorong artikulasi konflik ideologis dalam kerangka institusional. Pendekatan ini membuka ruang bagi revitalisasi politik melalui pemosisian ulang warga sebagai subjek politik aktif, bukan hanya objek kebijakan.
Implikasi Teoretis dan Metodologis
Secara teoretis, konsep post-democracy mengundang peninjauan ulang atas relasi antara negara, pasar, dan warga negara dalam teori politik. Ia menunjukkan bahwa demokrasi bukanlah entitas statis, tetapi medan kontestasi yang selalu rentan terhadap kooptasi kekuasaan non-demokratik. Ini juga menantang dikotomi klasik antara state dan civil society, sebab dalam praktik post-democratic, banyak institusi sipil justru tersubordinasi pada logika pasar.
Secara metodologis, riset-riset tentang post-democracy menuntut pendekatan multidisipliner: menggabungkan kajian politik institusional, ekonomi politik, analisis media, hingga studi budaya. Peneliti perlu melihat demokrasi tidak hanya sebagai kerangka hukum, tetapi sebagai pengalaman sosial yang konkret—terutama dari perspektif kelompok rentan.
Ruang Riset Mahasiswa
Dalam konteks pengajaran dan pembinaan riset mahasiswa, post-democracy menawarkan berbagai objek studi yang relevan:
- Studi peran elite bisnis dalam pemilu daerah
- Analisis komunikasi politik berbasis data dan logika branding
- Hubungan antara partai politik dan kepentingan modal
- Politik representasi dalam media digital
- Persepsi masyarakat terhadap demokrasi prosedural
- Pemolisian wacana publik melalui UU ITE atau instrumen hukum lainnya
Teori ini sangat cocok ditempatkan dalam domain filsafat politik dan sosiologi politik, terutama untuk mengevaluasi ulang asumsi-asumsi normatif demokrasi serta memahami dinamika kekuasaan yang tersembunyi dalam ranah yang tampak demokratis.
Konsep Post-Democracy mengajak kita untuk tidak terjebak pada penampilan formal demokrasi. Demokrasi bukanlah sekadar soal pemilu dan parlemen, tetapi tentang bagaimana kekuasaan diproduksi, didistribusikan, dan dipertanggungjawabkan. Dalam dunia yang ditandai oleh kuasa korporasi, disinformasi digital, dan depolitisasi publik, memahami post-democracy menjadi langkah awal untuk merumuskan demokrasi yang lebih radikal, partisipatif, dan substantif.