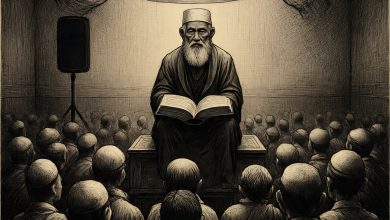Decolonial Theory: Menggugat Epistemologi Modernitas dan Membangun Kosmologi Pluriversal

Decolonial Theory berakar pada kritik terhadap modernitas sebagai proyek global yang dihasilkan oleh kolonialisme Eropa. Berbeda dari postcolonial theory yang berkembang di ruang-ruang studi sastra dan representasi (misalnya Edward Said atau Homi Bhabha), decoloniality berkembang dari tradisi kritik epistemologis, sosiologi pengetahuan, dan sejarah dunia (world-systems theory), khususnya dari pengalaman kolonial Amerika Latin dan Afrika.
Salah satu pencetus utamanya adalah Aníbal Quijano, yang memperkenalkan konsep coloniality of power pada akhir 1990-an. Quijano berargumen bahwa kolonialisme tidak pernah benar-benar berakhir: meskipun penjajahan formal telah selesai, struktur kekuasaan kolonial tetap bertahan dalam bentuk kolonialitas yakni cara dunia diatur, dikelola, dan dipahami melalui logika rasial, kapitalistik, dan Euro-sentris. Kolonialitas ini hidup dalam sistem pengetahuan, pembagian kerja global, dan narasi sejarah yang menghapuskan pengalaman Global South.
Teori ini kemudian dikembangkan oleh Walter Mignolo, Nelson Maldonado-Torres, Boaventura de Sousa Santos, dan para sarjana dekolonial lainnya yang menyusun kerangka konseptual berbasis:
Coloniality of power: dominasi ekonomi-politik melalui rasialisasi dan eksploitasi global.
Coloniality of knowledge: hegemoni pengetahuan Barat sebagai satu-satunya bentuk "ilmu" yang sah.
Coloniality of being: pengingkaran terhadap subjektivitas dan kemanusiaan masyarakat non-Barat.
Epistemic disobedience: tindakan pembangkangan terhadap tatanan pengetahuan kolonial-modern.
Pluriversality: cita-cita membangun dunia yang tidak homogen, tapi ditopang oleh keragaman epistemik yang setara.
Dengan demikian, dekolonialitas bukan sekadar proyek kritik, tetapi sebuah praksis pembebasan epistemik.
| Unsur / Konsep Kunci | Penjelasan Ringkas | Kutipan Langsung (Mignolo/Quijano) | Karya & Tahun |
|---|---|---|---|
| 1. Coloniality of Power | Kolonialisme berlanjut dalam bentuk struktur pengetahuan, ekonomi, dan identitas. | “Coloniality survives colonialism.” | Aníbal Quijano, Coloniality of Power, 2000 |
| 2. Epistemic Disobedience | Perlawanan bukan hanya politis, tapi juga kognitif: membongkar cara berpikir kolonial. | “To decolonize knowledge is to decolonize being.” | Walter Mignolo, The Darker Side of Western Modernity, 2011 |
| 3. Modernitas sebagai Kolonialitas | Modernitas tidak netral, tetapi bagian dari proyek dominasi global Barat. | “Modernity is a colonial matrix of power.” | Mignolo, The Idea of Latin America, 2005 |
| 4. Geo- dan Body-Politics of Knowledge | Pengetahuan harus dikembalikan ke konteks tubuh dan ruang non-Barat. | “All knowledge is geo- and body-politically located.” | Mignolo, 2009 |
| 5. Pluriversality vs Universalitas | Menolak satu kebenaran universal; merayakan keberagaman cara hidup dan berpikir. | “Decoloniality affirms pluriversality as a universal project.” | Mignolo, 2011 |
Kontekstualisasi di Indonesia: Negara Postkolonial yang Masih Terjajah Epistemiknya
Di Indonesia, warisan kolonial dapat dibaca melalui cara kita memahami demokrasi, hukum, pendidikan, hingga kategori politik. Setelah kemerdekaan, elite nasional menggantikan penjajah, tetapi sistem pengetahuan, birokrasi, dan nilai-nilai modern tetap didasarkan pada struktur kolonial Belanda dan logika barat. Bahasa akademik kita sarat dengan "pengetahuan impersonal", narasi modernisasi, dan pemujaan terhadap metodologi ilmiah-positivistik.
Hal ini terlihat dalam beberapa dimensi:
Sistem pendidikan politik yang lebih mengajarkan liberalisme klasik dan konstitusionalisme Barat daripada tradisi politik lokal seperti musyawarah, syura, atau falsafah keadilan Nusantara.
Negara hukum dan demokrasi prosedural yang diukur dari indikator-indikator eksternal (misalnya Freedom House atau EIU) tanpa memperhitungkan konteks kultural dan historis Indonesia.
Ilmu sosial kita banyak menjadikan teori-teori seperti Weberian bureaucracy, liberal democratic theory, atau modernization theory sebagai standar, sementara pemikiran politik lokal jarang diposisikan sebagai sumber teori.
Dalam hal ini, dekolonialitas mengajak kita untuk tidak hanya mengganti sumber kutipan, tetapi merekonstruksi cara berpikir dan membangun struktur pengetahuan baru yang berpihak pada pengalaman sejarah kita sendiri.
Kritik dan Alternatif
Meski membawa daya radikal, teori dekolonial tidak lepas dari kritik. Beberapa kritik akademik yang penting adalah:
- Risiko esensialisasi: dalam upaya menggali kembali identitas lokal atau “kearifan budaya,” beberapa proyek dekolonial jatuh ke dalam glorifikasi masa lalu yang tidak kritis, atau essentialisme budaya yang mengabaikan perubahan sosial internal.
- Bahaya relativisme: ketika semua sistem pengetahuan dianggap setara, bagaimana kita membedakan antara pengetahuan yang menindas (misalnya sistem kasta) dan pengetahuan yang membebaskan?
- Kurangnya kerangka institusional: dekolonialitas sebagai wacana masih minim dalam memformulasikan mekanisme konkret pembaharuan kelembagaan negara atau sistem pendidikan.
Sebagai alternatif, para pemikir seperti Santos mengusulkan apa yang ia sebut epistemologies of the South, yaitu penggabungan antara pengetahuan rakyat (popular knowledge), tradisi lokal, dan prinsip-prinsip emansipatoris. Mignolo menekankan pentingnya border thinking—berpikir dari batas (dari pinggiran sistem), bukan dari pusat hegemoni epistemik.
Implikasi Teoritis dan Metodologis serta Ruang Riset Mahasiswa
Secara teoritis, dekolonialitas menantang:
- Monopoli universalitas Barat: menolak asumsi bahwa ilmu pengetahuan harus netral, objektif, dan bebas nilai menurut standar rasionalitas Eropa.
- Dikotomi modern vs tradisional: membuka ruang bagi ko-eksistensi antara logika rasional-instrumental dan kosmologi lokal atau spiritualitas komunitas.
- Definisi “kemajuan” dan “demokrasi”: mendorong narasi alternatif tentang modernitas yang tidak mesti sekuler, liberal, atau individualistis.
Secara metodologis, pendekatan dekolonial mendorong:
- Metodologi partisipatif dan kontekstual: penelitian dilakukan bersama komunitas, bukan atas mereka.
- Pengakuan terhadap positionality: peneliti harus menyadari dari mana ia berpikir, siapa yang ia representasikan, dan siapa yang disenyapkan.
- Riset transdisipliner dan kosmopolit lokal: mencampurkan pendekatan etnografi, sejarah lisan, studi naskah, dan praktik budaya.
Mahasiswa dapat mengembangkan riset-riset seperti:
- Studi terhadap pengalaman komunitas adat dalam menghadapi pembangunan (misalnya IKN, proyek tambang, atau food estate).
- Kajian terhadap tradisi intelektual lokal, seperti pesantren, tarekat, atau pemikiran tokoh seperti Hamka, Nurcholish Madjid, dan Syafi’i Ma’arif sebagai bentuk epistemologi non-Barat.
- Kritik terhadap silabus ilmu sosial di Indonesia dan desain kurikulum alternatif berbasis epistemologi lokal.
- Studi terhadap representasi minoritas dan kelompok pinggiran dalam kebijakan, media, atau buku teks.
- Kajian tentang bahasa kekuasaan dan pemaknaan konsep politik dalam bahasa lokal, seperti “amanah”, “musyawarah”, atau “rakyat” sebagai epistemik site yang membentuk struktur berpikir masyarakat.
Teori dekolonial tidak sekadar mengajarkan kritik terhadap kolonialisme masa lalu, tetapi menyadarkan kita bahwa cara berpikir, mengajar, dan meneliti hari ini pun masih bisa menjadi bagian dari kolonialitas. Ia mengajak kita untuk meninjau kembali siapa yang memiliki kuasa untuk menentukan apa itu ilmu, siapa yang disebut intelektual, dan bagaimana masyarakat didorong untuk memahami dirinya sendiri.
Dengan pendekatan ini, ruang studi politik Indonesia dapat dibuka lebih lebar bagi bentuk-bentuk kebijaksanaan, demokrasi, dan keadilan yang selama ini dianggap “tidak ilmiah” hanya karena tidak sesuai dengan logika dominan. Itulah tugas mendesak generasi intelektual baru: bukan hanya belajar dari teks-teks Eropa, tetapi juga membongkar hegemoni epistemiknya dan membangun teori dari Selatan.